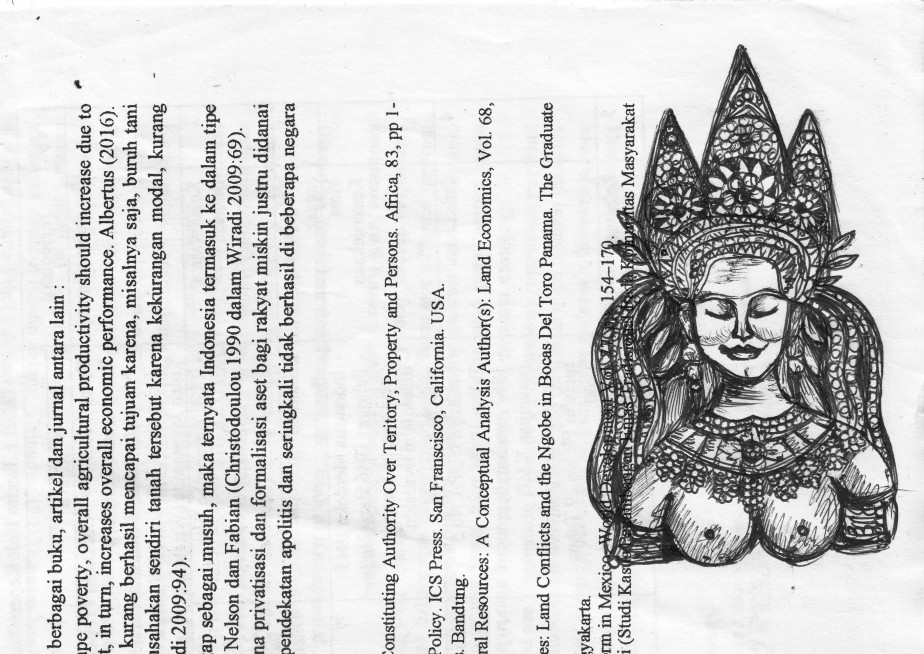
Halo. Saya masih melanjutkan ulasan CASI kemarin. Mungkin saya cuman kangen kuliah dan bikin jurnal-jurnalnya (yang dulu saya suka malas bikin) ya, jadi ketika ada kuliah gratis (plus makan gratis #ehe #dansponsornyamengakuhambaallah) niatan untuk mencatatnya kembali saya tuntaskan, meskipun sangat telat dari rencana awal.
Anyway, di bagian selanjutnya kami mendengarkan pemaparan dari para peneliti yang tengah melakukan residensi di ARC, yakni Ahmad Tridakusumah yang meneliti soal Land Reform di Kadupandak dan Lian Sinclair yang sedang menulis tesis tentang kasus Land-Grabbing di Kulon Progo. Juga ada Hendro Sangkoyo atau Mas Yoyok dari School of Democratic Economics (SDE) yang membredel perubahan konteks persoalan politik-tani dan ekologi di paruh kedua 1960an.
Terakhir, ada ulasan Pak Dianto soal gerakan sosial dan kunjungannya ke MST Brazil, sebagai referensi alternatif metodologi pergerakan melawan rezim neoliberal. Tapi saya tidak akan menjelaskan soal MST disini. Karena kalian bisa langsung mengunjungi web mereka, dan Pak Dianto menyatakan sedang mulai menyusun draft tulisan tentang kunjungan dan update terkini terkait MST. Atau kalian bisa ikutan Kelas CASI mendatang dan berdialog langsung tentangnya.


