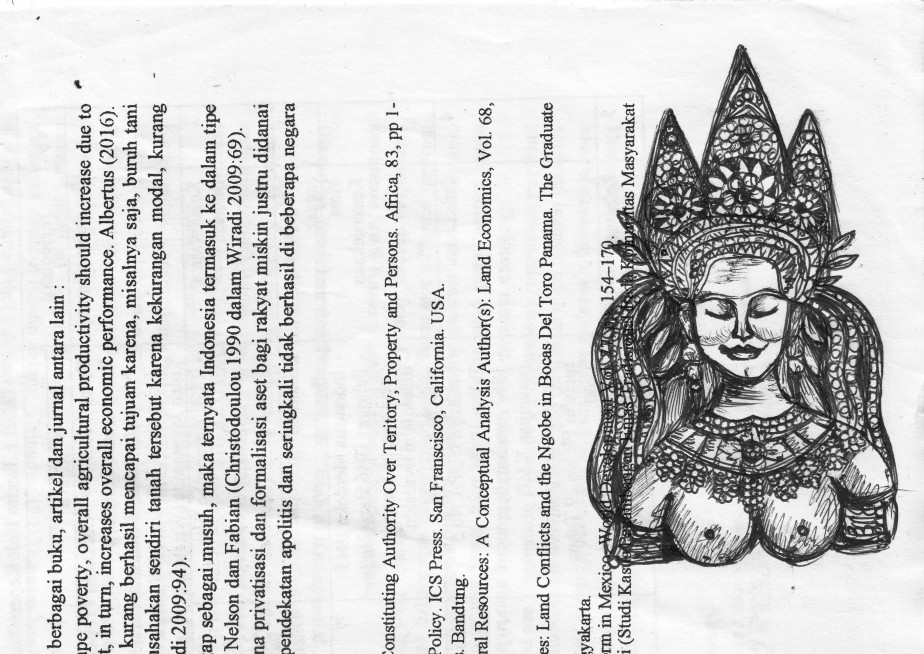
Halo. Saya masih melanjutkan ulasan CASI kemarin. Mungkin saya cuman kangen kuliah dan bikin jurnal-jurnalnya (yang dulu saya suka malas bikin) ya, jadi ketika ada kuliah gratis (plus makan gratis #ehe #dansponsornyamengakuhambaallah) niatan untuk mencatatnya kembali saya tuntaskan, meskipun sangat telat dari rencana awal.
Anyway, di bagian selanjutnya kami mendengarkan pemaparan dari para peneliti yang tengah melakukan residensi di ARC, yakni Ahmad Tridakusumah yang meneliti soal Land Reform di Kadupandak dan Lian Sinclair yang sedang menulis tesis tentang kasus Land-Grabbing di Kulon Progo. Juga ada Hendro Sangkoyo atau Mas Yoyok dari School of Democratic Economics (SDE) yang membredel perubahan konteks persoalan politik-tani dan ekologi di paruh kedua 1960an.
Terakhir, ada ulasan Pak Dianto soal gerakan sosial dan kunjungannya ke MST Brazil, sebagai referensi alternatif metodologi pergerakan melawan rezim neoliberal. Tapi saya tidak akan menjelaskan soal MST disini. Karena kalian bisa langsung mengunjungi web mereka, dan Pak Dianto menyatakan sedang mulai menyusun draft tulisan tentang kunjungan dan update terkini terkait MST. Atau kalian bisa ikutan Kelas CASI mendatang dan berdialog langsung tentangnya.
Bagian II
Studi Kasus 1: Land Reform di Kadupandak
Trida mempelajari bagaimana negara, pihak swasta, dan petani berperan dalam proses transformasi struktur pre kapitalistik menuju kapitalistik. Untuk menjelaskan dinamika dan penguasaan tanah di Kadupandak, ia menggunakan konsep rezim hak kepemilikan (property right regimes) dengan kategori state property, common property, dan open access. Ia memulai penelusurannya akan rezim hak milik dan penguasaan tanah di Kadupandak sejak era pra kolonial—bagaimana hutan belantara dapat diakses secara relatif terbuka oleh siapapun (open access) ketika menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran dan Mataram, dan tetap bisa dimasuki serta digunakan oleh rakyat untuk berburu, mengumpulkan kayu, dan lain sebagainya. Kontrak 25 Februari 1677 antara Mataram dan VOC membuat kawasan tersebut dikuasi oleh VOC (secara de jure) dan Senapati Cianjur (secara de facto).
Pemisahan secara lebih tegas dalam rezim hak milik nampak saat kolonialisme, dimana pemerintah kolonial memberlakukan Agrarische Wet 1870 untuk mengimplementasikan liberalisasi dan privatisasi lahan. Aktor swasta, Youngkinkonneng N.V., mulai menggunakan tanah di Kadupandak pada 1918 untuk bisnis perkebunan karet dan masyarakat desa sekitar menjadi buruh perkebunan. Beralih pada masa pendudukan Jepang, tuan-tuan tanah Belanda meninggalkan perkebunan, termasuk Youngkinkonneng N.V. sebagai pemilik 2.000-2.500 ha tanah perkebunan di Kadupandak. Masyarakat desa pun mulai menduduki dan memperluas tanah garapan untuk kehidupannya.
Pada masa awal kemerdekaan, Bung Hatta mulai mempromosikan gagasan koperasi untuk mengelola perkebunan besar (saya belum cek bagaimana gagasan koperasi yang ia maksud secara spesifik). Kemudian pada 1960, muncul UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Perkebunan. Pada masa itu, sempat ada klaim dari PT. Perboe terhadap tanah eks Youngkinkonneng N.V yang membuat masyarakat desa resah. Pada saat-saat ini pula masyarakat merintis irigasi Cidadali. Berlanjut pada era Orde Baru yang pro investasi dan memberlakukan Revolusi Hijau (tanpa RA), pemerintah tercatat menerbitkan HGU untuk PT. Cibogogeulis, PT. Banyusagara, dan PT. BJA. Masyarakat sempat memperoleh redistribusi lahan sebanyak 313,6 ha, namun kerapkali mendapatkan intimidasi, pengrusakan lahan garapan yang dianggap berada di wilayah perusahaan, mengalami bentrokan fisik dan kriminalisasi. Atas dasar itulah, Paguyuban Petani Cianjur (PPC) didirikan dengan tujuan kembali mendapatkan hak menggarap dan mengelola tanah.
Pada era SBY, seperti disebutkan sebelumnya, pemerintah mencetuskan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan menerbitkan PP No. 11 tahun 2011 tentang tanah terlantar sebagai dasar hukum BPN untuk melakukan pemetaan penguasaan tanah, sebagai pendukung PPAN. PT. BJA saat itu menggarap sebagian tanah, sementara sebagian lainnya terlantar. 528,5 ha tanah eks HGU pun dikuasai oleh 2.000 RTP Kadupandak, namun PT. BJA merespon dengan melakukan pematokan lahan-lahan eks HGU PT. Banyusagara dan Cibuni Cipongkok. Penggarap lahan juga harus mengisi formulir yang menyatakan pengakuan bahwa tanah yang digarap adalah HGU PT. BJA. PPC mulai berjejaring dengan NGO di tingkat regional, nasional, dan internasional, sementara bentrokan fisik mulai terjadi di lapangan. Para petani pun melakukan unjukrasa untuk menuntut hak menggarap dan mengelola lahan, serta membatalkan proses tukar guling antara PT. BJA dan Perum Perhutani, hingga menuntut “Land Reform”.
Beralih pada masa Nawacita Jokowi, Strategi Pelaksanaan RA kembali digulirkan. BPN dan Bupati Cianjur mengklaim berkomitmen terhadap RA. Dinas Pertanian menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait. Saat ini, tanah tergolong “terlantar” oleh pihak swasta, sehingga masyarakat di Kadupandak melakukan pengukuran tanah partisipatif, membuat irigasi, dan membangun jalan serta permukiman. Mereka mengajukan permohonan sertfikasi tanah garapan kepada Bupati Kab. Cianjur pada 27 September 2016, melakukan pertemuan dengan BPN Jabar bersama 5 organisasi tani lain di Jabar pada 24 Juli 2017, menggelar unjukrasa petani menuntut percepatan sertifikasi tanah, serta melakukan pengorganisasian dan pelatihan bagi para petani. Pertanyaannya, bagaimana prospek sertifikasi tanah tidak terjebak dalam logika “apolitisme” dan privatisasi ala neoliberal? Karena seperti dibahas sebelumnya, redistribusi tanah tanpa institusi pendukung hanya akan berujung pada logika privatisasi lahan yang menimbulkan ketimpangan pada masyarakat tani.
Seminimalnya, penelitian Bung Trida telah memetakan secara kronologis rezim kepemilikan tanah di wilayah Kadupandak yang dapat menjadi arsip dan referensi.
Studi Kasus 2: Strategi Land-Grabbing
Selanjutnya, ada Lian yang memaparkan penelitiannya tentang konteks politik neoliberal terkait sumber daya alam dalam konflik Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) dengan megaproyek tambang pasir besi dari Jogja Magasa Iron, sebuah perusahaan berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang dimiliki PT. Jogja Magasa Mining dari Indonesia (30%) dan Indomines Limited dari Australia (70%). Sebagai kandidat Ph.D Universitas Murdoch dan warga Australia, Lian menjelaskan bagaimana peranan dan strategi perusahaan-perusahaan investasi pertambangan dari Australia dalam konflik agraria dan kasus-kasus pencaplokan lahan di Indonesia. Selain di Kulon Progo, ia meneliti juga soal ini di Gosowong (Maluku Utara) dan Kelian (Kalimantan Timur).
Lian memulai pemaparannya dengan pembacaan struktur kapitalisme oligarki Indonesia. Pasca reformasi, oligarki Orde Baru mereorganisasi (dan menyesuaikan diri) terhadap gelombang demokratisasi dan desentralisasi. Mereka menjaga kekuasaan melalui berbagai macam jalur, mulai dari parlemen, kolusi, politik uang hingga politik SARA, mengambil aset negara untuk diprivatisasi, dan menjalin kemitraan dengan memfasilitasi atau mengambil modal internasional. Gelombang baru membeli dan mengambil aset asing ini seiring dengan keterbukaan pasar. Perilaku oligarki yang oportunistik, liberal, dan predator bagaimanapun cocok dengan kapital neoliberal, bahkan bersifat mutualistik.
Kasus yang paling populer adalah bagaimana Freeport di Papua Barat diuntungkan dengan keberadaan dan kekerasan TNI. Di satu sisi, TNI membuat dasar legitimasi keberadaan dan kekerasannya melalui manipulasi sosial-politik—sembari mendapat bayaran dari Freeport atas “pengkondisian” yang mereka lakukan. Sementara di lain sisi, Freeport seolah-olah terlepas dari tanggungjawab atas tindak kekerasan yang dlakukan oleh TNI, terlihat sebagai perusahaan yang “baik” di pers dan media—karena anggapan umum yang melihat sumber masalah adalah selalu aparatur pemerintah setempat yang korup.
Berdasarkan proposal risetnya, Lian secara khusus tertarik pada mekanisme pencaplokan lahan di era neoliberal yang menggunakan strategi (1) aliansi domestik dan (2) cara-cara partisipatif. Dengan aliansi domestik, perusahaan multinasional beraliansi dengan elit institusi setempat agar perusahaan tidak harus secara langsung melakukan kekerasan atau “kerjaan lapangan” lainnya (seperti kasus TNI ❤ Freeport tadi). Pekerjaan semacam itu biarlah dilakukan oleh polisi, TNI, preman, serta perangkat hukum yang berlaku.
Sedangkan, cara-cara “partisipatif” ditempuh perusahaan melalui program-program CSR, misalnya pengembangan komunitas, pembentukan koperasi desa, atau merekrut warga setempat. Partisipasi dalam proses-proses korporat semacam ini mulai populer dalam era “political correctness” liberal seperti hari-hari ini. Dalam menanggapi protes komunitas setempat, misalnya, PT. Indo Mines banyak menjalankan proses konsultasi dan kompensasi bersama warga—dan tak jarang banyak yang termoderasi.
Dalam sesi diskusi, Pak Hu, salah satu peserta dari Pati menceritakan pengalaman serupa warga Pati ketika berhadapan dengan perusahaan semen. Perusahaan seringkali meriset aktor-aktor gerakan perlawanan di daerah tersebut dan menggunakan beberapa “eks-aktivis” untuk mengelola program pemberdayaan CSR, yang tak jarang pola dan kontennya mencatut program-program dari gerakan perlawanan. Mereka melacak bagaimana akar kekerabatan aktor-aktor pergerakan setempat, sehingga menjadi tidak mengherankan kontur konflik di aras horizontal menjadi kian kompleks. Menggunakan forum agama dan tokoh-tokoh NU (dalam kasus Pati) untuk menghalalkan proyek perusahaan juga menjadi cara-cara tipikal bagi perusahaan.
…
Dalam konteks neoliberalisasi inilah, Dianto melanjutkan pembahasan dengan abstraksi persoalan Land-Grabbing atau Pencaplokan Lahan, yang ia definisikan sebagai transfer penguasaan lahan skala besar—dengan cara apapun—kepada korporasi, baik perusahaan domestik maupun asing, dan seringkali bersifat lintas batas untuk tujuan investasi dan mencari keuntungan (baik dengan alasan ekonomi hingga ekologi)—dengan mengabaikan hak warga setempat untuk memelihara keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, atau keterlibatan mereka dalam memelihara lingkungan.
Dalam kurun waktu 1998-2004, terjadi praktik pembersihan elemen-elemen yang dianggap mengganggu pasar dan kapital oleh kekuasaan internasional di Indonesia (seperti Bank Dunia dan IMF). Reformasi, dengan demikian, bukan hanya terjadi (secara monolitik dan eksklusif) karena mahasiswa menduduki gedung DPR menuntut pengunduran diri Soeharto, namun karena dorongan konteks ekonomi-politik internasional yang lebih luas. Tanpa bermaksud mendiskreditkan gerakan perlawanan terhadap Orba, inilah salah satunya yang menjelaskan mengapa pasca reformasi kapital justru semakin mutakhir mereorganisasi diri. Penciptaan kekuatan politik yang dominan diperlukan untuk menciptakan iklim yang baik untuk investasi dan bisnis, alias memperlancar akumulasi kapital dan menghilangkan kontradiksi negara-pasar.
Pencaplokan lahan biasanya mengikuti alur berikut: penetapan dan/atau perubahan fungsi kawasan, pemetaan, serta regulasi perundangan dijadikan dasar penerbitan ijin-ijin usaha dan hak atas tanah untuk tujuan komersial dan kontrak-kontrak operasi. Transaksi lahan dan/atau alih penguasaan tanah selanjutnya dilakukan dan operasi industri atau eksploitasi dimulai. Penggusuran dan pemindahan warga sekitar pun dianggap sebagai konsekuensi business as usual dalam skema ini. Kejahatan konstitusional, korupsi, kejahatan kemanusiaan dan lingkungan dengan demikian menjadi fitur inheren dalam skema pencaplokan lahan.
Sehubungan dengan penetapan ulang fungsi kawasan dan pemetaan, penataan ruang (spatial zoning) dalam skema neoliberal merupakan cara untuk menciptakan batas-batas legal eksploitasi tanah/sumberdaya. Atau kembali menengok Lefebvre dalam Production of Space (1905) yang melihat penataan ruang sebagai sebuah reproduksi ruang dalam konteks kontrol, dominasi, dan akumulasi kapital. Dengan demikian, enclosure (pemagaran) kembali dilakukan di era yang katanya posmodern kontemporer ini—plus secara legal dan “demokratik”.
Untuk melegitimasi tindakan-tindakan tersebut, narasi andalan “Krisis Global” neoliberal pun digulirkan, yakni krisis food, fuel, finance (makanan, bahan bakar, keuangan) yang meliputi sektor riil dan industri nabati untuk dalih pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Reproduksi ruang melalui MP3EI, Undang-Undang Percepatan Infrastruktur, Public Private Partnership (PPP), dan Transit Oriented Development (TOD) dilandaskan pada narasi tersebut. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah salah satu contoh bagaimana narasi krisis global direproduksi dan digunakan untuk legitimasi megaproyek dan perampasan lahan besar-besaran.
Menemukan Cara Bertutur Tandingan dalam Orde Politik-Tani Kekinian
SDE, atau dalam Bahasa Indonesia Sekolah Ekonomika Demokratik, merupakan sebuah sekolah yang bertujuan untuk mencari cara bertutur tandingan bagi entitas sosial-ekologis-menyejarah, di tengah sektoralisme dalam gerakan seperti hari-hari ini. Mas Yoyok membicarakan tulisannya, “Politik Tani di Indonesia”, untuk mempertanyakan kembali premis Reforma Agraria di hadapan Ko-Evolusi Kapital. Masih berhubungan dengan strategi-strategi kapital untuk mempermainkan political correctness tadi, penting mempertanyakan bagaimana membangun tuturan tandingan di tengah “tuturan vulgar” seperti sekarang.
Namun sebelum menjawab hal tersebut, kita perlu mempersoalkan pembacaan kita terhadap rerantai produksi-konsumsi biologis dan dinamika relasi sosial-ekologisnya, atau yang selanjutnya diacu sebagai “Politik-Tani”. Mas Yoyok melakukan pembacaan secara lebih mendetail soal pemutarbalikan logika-sosial kedaulatan politik-tani, dari perumusan rancangan UUPA 1960 (yang meskipun masih jauh dari selesai dan dalam perdebatan, setidaknya bernafas “populis”) menjadi orde politik-tani dalam kerangka rasionalitas negara dan ekonomi neoklasik, dan yang kemudian menjadi subordinat semata dari perluasan domain akumulasi kapital. Melalui tiga ketentuan politik berkekuatan hukum, yakni (1) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, (2) UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dan (3) UU No. 11/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, negara menandai rasionalitas baru atas ruang-waktu teritorialnya.
Dengan diberlakukannya UU No.5/1967, seluruh wilayah hutan menjadi “dikuasai negara”, termasuk hutan-hutan yang dikuasai dan dipersepsi oleh masyarakat adat dan perangkat-pengetahuannya sebagai hutan adat. UU tersebut pun dibuat atas dasar upaya memenuhi permintaan dari luar negeri akan ekspor hasil hutan dan permintaan industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku. Sedangkan UU No. 11/1967 menghapus ketentuan pelaku pertambangan yang harus berkewarganegaraan Indonesia atau pengurusnya warga negara Indonesia seutuhnya, yang tertuang dalam UU/Perpu No. 37/1960. Semuanya ini kemudian ditekankan dengan UU No.1/1967 yang memfasilitasi investasi asing, sehingga mengintegrasikan ruang hidup masyarakat yang dikuasainya pada rerantai produksi-nilai global.
Pembalikan logika politik ini tidak hanya berlaku bagi lahan pertanian dan hutan di daratan, tetapi juga wilayah perairan dan udara. Rantai suplai pertambangan hidrokarbon adalah salah satu contoh paling masif, dimana minyak bumi dan gas alam dieksploitasi tanpa mempertimbangkan metabolisme sosial-ekologis situs ekstraksi. Tak hanya dimensi ruang, data yang dikumpulkan Mas Yoyok menunjukkan bagaimana dimensi waktu turut tercaplok karena sebagian besar lahan caplokan tidak langsung digarap, tetapi dijadikan stok lahan yang diakumulasi, untuk kemudian digarap dan dioperasikan saat iklim ekonomi dianggap pas. Kedua dimensi ini salah satunya digabungkan untuk memproyeksikan peta potensi geologis dalam suatu wilayah kartografis untuk blok-blok operasi tambang minyak dan gas di masa depan. Ruang hidup masyarakat praktis diperlakukan sebagai “ruang sisa” dari situs-situs produksi surplus—seolah ruang-ruang hidup tersebut tidak terjejaringkan dengan sistem ekologi yang lebih luas.
Dalam mekanisme penyerapan surplus, kota-kota paling terurbanisasi seperti Jakarta menghisap surplus paling banyak tanpa ada redistribusi surplus yang sesuai, apalagi dapat memulihkan krisis di situs-situs ekstraksi. Dengan rantai suplai yang diorganisir dalam skala global dan secara terpisah-pisah tiap komponennya secara spesifik (atau yang biasa disebut Posfordisme), proses sosial-ekologis dan jejak ruang-waktu yang terlibat menjadi kabur dan hilang dari perhatian publik (apalagi dikombinasikan dengan perubahan tren produksi yang serba cepat). Yang muncul di permukaan hanyalah gejala-gejalanya saja, seperti kasus kemiskinan, krisis kesehatan, ataupun kebobrokan birokrasi—tanpa ada akses dan/atau pemahaman memadai untuk mengurai akar persoalannya.
Dalam era neoliberal, negara yang biasanya disebut-sebut tidak memiliki peranan lagi toh menemukan relevansinya justru untuk memegang kendali politik atas penduduknya dalam rangka perluasan medan integrasi produksi-konsumsi. Hal inilah yang dilihat Mas Yoyok dalam kerjasama regional yang mengagungkan kebebasan aliran kapital seperti ASEAN dan plus-plusnya. ASEAN++ menjadi mekanisme politik pencaplokan wilayah pulau-pulau besar sebagai situs produksi dan investasi “bersama” antar anggotanya. Ketika Asia Timur memasuki krisis sejak 1998, turunnya mata uang negara-negara anggota ASEAN justru menjadi momen tepat untuk mengakuisisi lahan dan bisnis di negara-negara tersebut. Fragmentasi rantai-pasokan (supply chain) dalam kapitalisme posfordis pun menjadikan negara bukan lagi produsen “suatu barang”, melainkan “…sebagai pemasok fungsi dalam proses produksi dan rantai penciptaan nilai yang berkaki di banyak lokasi”[1].
Domain arena politik-tani terkini dengan demikian mencakup wilayah geografis yang terus meluas, dengan kontrol institusional yang kian rumit dan tumpang tindih. Mas Yoyok sempat memutarkan video para petinggi negara-negara “maju” yang mulai mengirim robot-satelit untuk memetakan potensi obyek planetari lain. Hal ini menunjukkan bagaimana menjaga kelangsungan akumulasi melalui perluasan domain spasial (sempat kepikiran ini mirip dengan Scramble for Africa yang dilakukan pada era kolonial). Tak hanya dari segi geografis, domain produksi-konsumsi pun mencakup bahan dan sumber energi yang meluas. Bukan hanya lahan tani dan “lahan produktif” saja, tetapi juga infrastruktur ekologis dan pendukung reproduksi manusia lainnya. Aliran kapital yang bebas dan cair justru mempermudah perampasan situs-situs tersebut dengan lebih gesit dan luput dari pengamatan komunitas sekitar ataupun publik.
Perkembangan ko-evolusi kapital sampai hari ini telah melampaui imajinasi di balik penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Pasalnya, sepetak lahan tidak lagi hanya dimaknai dari segi produktivitas tani, tetapi juga harus dihadapkan pada berlapis-lapis potensi rente, mulai dari kandungan mineral, hidrokarbon, hingga layanan fungsi alam (yang seringkali dimanfaatkan dan diperjualbelikan untuk membayar hutang emisi karbon). Logika kompensasi perusakan sosial-ekologis seperti ini seringkali berujung pada ilusi “penebusan dosa” melalui program-program pemberdayaan komunitas atau aktivitas semacam penghijauan (Alias asal kegelisahan “hati kecil” borjuis tenang—tanpa mengubah logika perluasan produksi-konsumsi bahan dan energi).
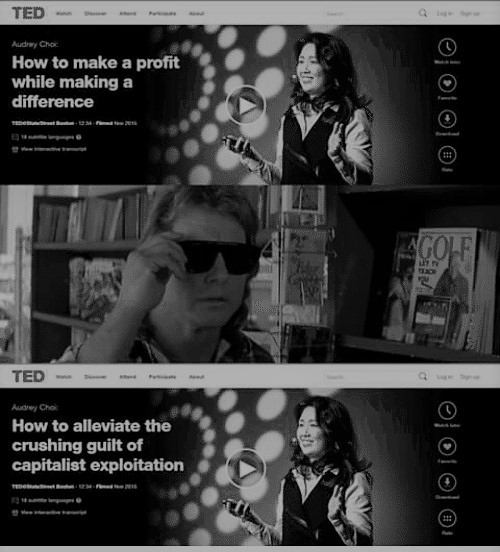
Selain itu, konteks sentral permasalahan relasi penghisapan oleh kelas pemilik tanah terhadap petani gurem dan buruh tani menjadi turut bergeser. Dengan logika (percepatan) Pembangunan-isme, negara memperbarui monopolinya atas ruang-waktu melalui pengambilalihan kepemilikan pribadi menjadi “untuk kepentingan umum”, dengan kompensasi yang seringkali tak layak. Petani gurem dan buruh tani dengan demikian menjadi makin dirugikan posisinya daripada sebelumnya. Dalam beragam kasus pencaplokan lahan, petani-petani penggarap tanpa tanah seringkali tak punya dasar hukum dan kepentingan seperti mereka yang memiliki tanah. Sementara posisi feodal pemilik absentee berhektar-hektar tanah tetap diamankan oleh skema kapitalisme neoliberal.
Dengan perkembangan-perkembangan tersebut, Beliau menyimpulkan bahwa politik-tani tandingan tidak akan cukup hanya dengan “…transfer aset lahan kepada subyek-subyek tani kecil/keluarga, melainkan juga harus merespon perubahan dalam moda operasi negara, pengurusan rerantai ekonomik, dan pengurusan publik”[2]. Pertanyaan lebih lanjut yang kita perlu ajukan terkait cara bertutur dan politik-tani tandingan menyangkut syarat-syarat belajar untuk memperbarui dan memperkuat perlawanan terhadap perusakan di tengah kecanggihan sirkuit kapital seperti sekarang, dimana redistribusi petak-petak produksi tani dan sertifikasi tanah bagi penggarap tidak lagi bersifat korektif. Di lain sisi, mengharapkan pemulihan krisis dari negara akan salah sasaran karena asal-usul kelas aparaturnya maupun telusur atas bangunan politisnya. Jangan-jangan memburuknya krisis-lah yang justru akan mendesak pekerja-tani untuk merebut syarat-syarat belajar, bertutur, dan berkehidupannya?
…
Akhirnya, tibalah di penghujung ulasan. Di akhir kelas, kami membahas bagaimana gerakan sosial berbeda dengan gerakan moral; bagaimana gerakan sosial menjadi sarana politik untuk mencapai tujuan sosial, penentang otoritas dan pembentuk masyarakat baru. Tujuan sosial politik yang tentunya berdasarkan proses sosial-ekologis menyejarah, dan ilmiah—alias bisa dipertanggungjawabkan. Pak Dianto juga menyampaikan tesisnya soal bagaimana dinamika keterlibatan dan posisi “urban intellectual” sebagai organisator dalam gerakan-gerakan tani di Indonesia; bagaimana hubungan saling tunggang-menunggangi dan gap kepentingan seringkali terjadi.
Hal ini saya rasa penting untuk kita diskusikan lebih lanjut di tengah atmosfer pergera’-geri’an (setidaknya yang banyak beredar di sekitar saya ((dan saya melihat dengan geuleuh diri saya saat berada di fase tersebut #sigh))) yang romantis dan moralis. Pasalnya, moralisme romantis (dan heroisme)-lah yang berkali-kali mengaburkan pembacaan kita atas konteks dan kondisi obyektif, sehingga menghasilkan strategi yang tidak relevan dan kontekstual, apalagi korektif.
[1] Sangkoyo, Hendro. 2017. “Politik Tani di Indonesia”, dibagikan pada peserta Pelatihan Critical Agrarian Studies of Indonesia (CASI) Kelas Lanjutan, 29 November – 2 Desember 2017, hlm. 10.
[2] Sangkoyo, Hendro. 2017. “Politik Tani di Indonesia”, hlm. 6.